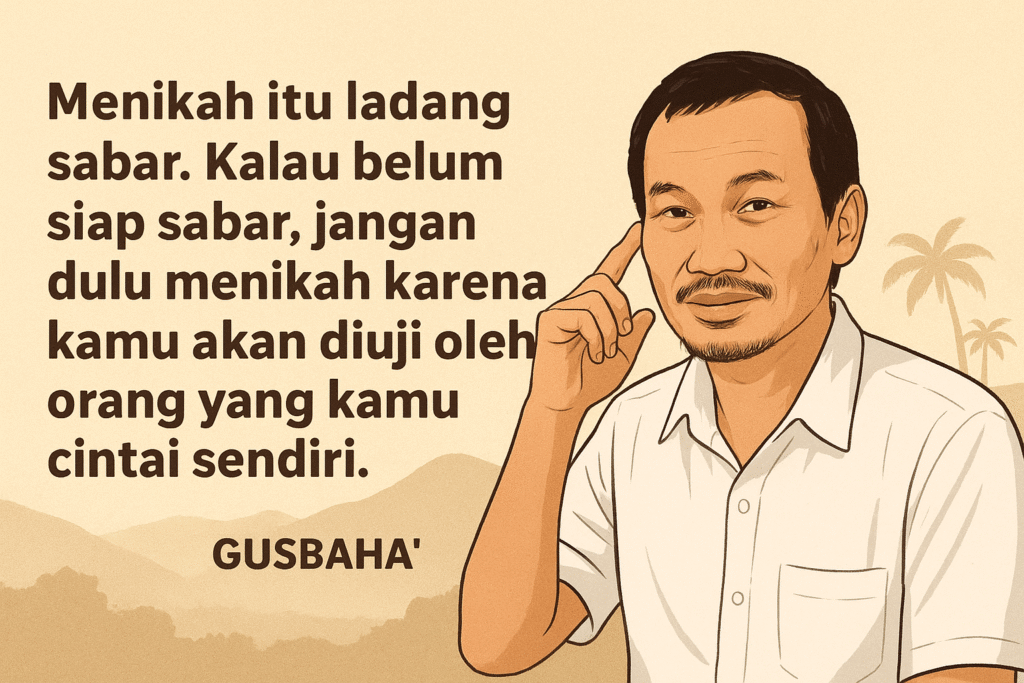
Menikah, Ladang Sabar, dan Tipu Daya Zaman Selfie
Oleh: Kang WeHa
Suatu ketika, KH. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha’) berpesan dengan bahasa yang sederhana tapi menghujam:
“Menikah itu ladang sabar. Kalau belum siap sabar, jangan dulu menikah. Karena kamu akan diuji oleh orang yang kamu cintai sendiri.”
Kalimat ini terasa seperti peringatan dini, terutama di zaman ketika pernikahan sering dipersempit maknanya: sekadar status, pesta, atau konten media sosial. Padahal, menikah justru awal dari ujian yang paling dekat dan paling lama.
Dalam Islam, pernikahan memang bukan janji hidup bahagia tanpa luka. Ia adalah proses menumbuhkan kesabaran. Maka Allah tidak mengatakan pernikahan itu langsung bahagia, tapi sakinah—ketenangan yang lahir dari upaya, bukan hadiah instan.
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya…”
(QS. Ar-Rum: 21)
Tenteram tidak datang dari pujian orang lain. Ia lahir dari kemampuan menahan ego, menutup aib, dan saling memaafkan. Di sinilah peringatan Gus Baha’ menjadi relevan dengan kondisi zaman akhir.
Gus Baha’ juga mengingatkan tentang tipu daya iblis yang halus tapi dahsyat di zaman ini—bukan lagi sekadar maksiat besar, melainkan hilangnya rasa malu dan rahasia pribadi:
“Inilah tipu daya iblis yang dahsyat di zaman akhir, membuat manusia tidak lagi punya rahasia pribadi. Lagi makan selfie, lagi jalan-jalan selfie, lagi ibadah selfie, bahkan ibadah di tanah suci pun sibuk selfie.”
Fenomena ini tampak sepele, tapi sesungguhnya berbahaya. Ibadah dan kehidupan pribadi yang seharusnya menjadi urusan batin, perlahan berubah menjadi tontonan. Bukan untuk syukur, melainkan pengakuan.
Rasulullah ﷺ sudah mengingatkan jauh sebelum media sosial lahir:
“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil.”
Para sahabat bertanya, “Apakah itu wahai Rasulullah?”
Beliau menjawab, “Riya’.”
(HR. Ahmad)
Di sinilah iblis bekerja rapi: mendorong manusia terlihat baik, bukan menjadi baik. Dari riya’ lahir ujub, dari ujub tumbuh kesombongan, dan akhirnya rasa malu terkikis.
Dalam rumah tangga, ini dampaknya lebih serius. Konflik tak lagi diselesaikan di dalam, tapi ditutupi demi citra. Aib pasangan bukan dijaga, tapi disimpan rapat demi feed yang tetap terlihat harmonis.
Padahal Nabi ﷺ bersabda:
“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah pasangan yang saleh.”
(HR. Muslim)
Kesalehan itu tidak diukur dari unggahan, tapi dari kesanggupan menjaga pasangan saat tidak ada yang menonton. Dari kesabaran saat kecewa. Dari kemampuan diam ketika ingin membela diri. Maka benar kata Gus Baha’: menikah itu ladang sabar. Dan sabar tidak pernah cocok dengan budaya pamer.
Jika seseorang belum siap diuji oleh orang yang ia cintai, belum sanggup menahan diri dari keinginan untuk selalu terlihat benar dan bahagia, barangkali yang belum siap bukan pasangannya—melainkan jiwanya sendiri.
Ngopi tanpa gula memang pahit.
Tapi dari pahit itulah kesadaran lahir.
